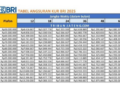Di tengah kompleksitas hukum pertanahan yang terus berkembang, nasib kelompok rentan, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), menjadi sorotan. Kebijakan pemerintah yang berencana menghapus status tanah Letter C, Letter D, atau Petok D, serta girik, mulai Februari 2026, berpotensi menciptakan ketidakadilan baru. Bagi mereka yang minim pendampingan hukum dan memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak, perubahan ini dapat berujung pada kehilangan aset vital, seperti rumah tempat tinggal.
Kisah Purnati dan Sukoyono: Tinggal di Tepi Tebing, Terancam Hilang Hak
Di sudut Kota Semarang, tepatnya di kawasan Kalilangse, Kelurahan Gajahmungkur, berdiri sebuah rumah sederhana yang berimpit dengan tebing. Di sanalah Purnati (49) dan Sukoyono (47) menjalani hidup mereka. Keduanya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tercatat dalam satu kartu keluarga. Rumah yang mereka tempati adalah warisan orang tua dengan status tanah garapan atau yang dikenal sebagai Letter D.
Kondisi kesehatan mental Purnati dan Sukoyono membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak atas tanah yang telah menjadi tempat bernaung mereka. Tanpa adanya pendampingan yang memadai, akses terhadap layanan pertanahan menjadi sebuah tantangan yang hampir mustahil untuk dihadapi secara mandiri.
Rumah bercat abu-abu kusam itu bukan hanya sekadar bangunan, melainkan satu-satunya tempat berlindung bagi keduanya. Untuk mencapainya, pengunjung harus menyusuri gang sempit yang hanya cukup dilalui oleh satu sepeda motor. Situasi semakin pelik ketika dua motor berpapasan dari arah berlawanan; para pengendara kerapkali harus mencari celah agar tidak bersenggolan, terutama mengingat kontur jalan yang menurun dan cukup curam. Posisi rumah yang berada di bawah turunan dari jalan utama menambah kesan tersembunyi dan terpencil.
Eko Subroto: Ayah Angkat yang Berjuang di Usia Senja
Di balik keseharian Purnati dan Sukoyono, ada sosok Eko Subroto (61), seorang ayah angkat yang telah merawat mereka sejak Mbah Soemari Djojo Soemarjo meninggal dunia pada tahun 2019. Kini, di usianya yang semakin menua, Eko Subroto dihadapkan pada beban berat untuk mengurus legalitas tanah di tengah keterbatasan fisik dan ekonomi.
Saat ditemui di rumahnya, Eko Subroto mengaku kebingungan harus memulai dari mana. Ia menyadari bahwa status Letter D tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah, namun proses sertifikasi tanah bukanlah perkara yang mudah.
“Saya ini sudah tua, tenaganya tidak seperti dulu. Tapi kalau bukan saya yang mengurus, siapa lagi? Mereka tidak punya siapa-siapa,” ujar Eko Subroto dengan suara parau. Ia melanjutkan, “Saya hanya ingin mereka tidak kehilangan rumah.”
Menurut Eko Subroto, pengurusan sertifikat tanah memerlukan banyak berkas, biaya yang tidak sedikit, serta waktu yang panjang untuk menempuh tahapan birokrasi yang berbelit. Ia juga mengkhawatirkan harus bolak-balik mengurus ke kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Takut nanti biayanya besar. Ngurusnya juga ribet,” keluhnya.
Status Menggantung: Ancaman Penghapusan Letter D
Rencana penghapusan status Letter D pada tahun 2026 menjadi momok tersendiri bagi Eko Subroto. Jika tanah tersebut tidak segera disertifikatkan, status hukum rumah yang ditempati Purnati dan Sukoyono akan menggantung.
“Rumah ini peninggalan orang tua mereka. Saya hanya merawat. Tapi nanti kalau Letter D dihapus dan tidak ada sertifikat, saya takut, (mereka) dianggap tidak punya hak. Yang rugi mereka, bukan saya,” ungkapnya dengan nada cemas.
Eko Subroto berharap, pemerintah tidak hanya menetapkan aturan baru, tetapi juga menyediakan pendampingan khusus bagi keluarga rentan. “Kalau bisa ada yang membantu dari pemerintah, ada pendampingan. Saya sudah tidak kuat kalau harus bolak-balik mengurus sendiri,” pintanya.
Di tengah warga Kalilangse lain yang memilih menunda sertifikasi karena mahalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), keluarga ODGJ ini menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. “Saya hanya ingin rumah ini tetap jadi tempat tinggal mereka sampai kapan pun. Kasihan kalau nanti dianggap tidak punya kekuatan hukum,” ujar Eko Subroto.
Pada usianya yang terus menua, Eko Subroto sebenarnya ingin menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Namun, tanggung jawab terhadap dua orang yang ia anggap seperti anak sendiri membuatnya terus bertahan. “Kalau saya sudah tidak ada nanti, siapa yang menjaga mereka? Makanya saya ingin urusan tanah ini selesai. Itu saja, supaya tenang,” imbuhnya, menunjukkan betapa besar harapannya agar masa depan Purnati dan Sukoyono terjamin.
Upaya Keluarga: Menyiapkan Legalitas Baru
Menyadari kompleksitas situasi, Ketua RT 5 RW 2 Kalilangse, Eko Ngadiyanto, menyatakan bahwa persoalan ini masih berada di ranah keluarga besar. Rumah yang ditempati oleh Purnati dan Sukoyono sejatinya merupakan bagian dari warisan turun-temurun.
Keluarga besar kini berupaya menyiapkan legalitas baru agar rumah tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sebelum status Letter D dihapus. “Rencananya suratnya mau dibuat dua. Nama Purnati dan saudaranya (yang sehat mental) untuk keamanan. Karena cucunya Mbah Sumar itu banyak. Dikasihkan ke salah satu cucu yang terpandang,” jelas Eko Ngadiyanto.
Proses ini belum sepenuhnya berjalan. Keluarga masih menunggu kedatangan salah satu cucu dari anak kedua almarhum Mbah Soemari, yang disebut sebagai pemilik hak sah atas rumah tersebut. “Saya kumpulkan keluarganya dulu, supaya enggak timbul miskomunikasi. Haknya sudah pasti,” tandas Eko Ngadiyanto, menegaskan komitmen keluarga untuk melindungi aset warisan bagi Purnati dan Sukoyono.
Implikasi Lebih Luas: Kebutuhan Pendampingan Hukum bagi Kelompok Rentan
Kisah Purnati, Sukoyono, dan Eko Subroto mencerminkan potret kerentanan yang lebih luas di masyarakat. Penghapusan status tanah Letter D, meskipun bertujuan untuk modernisasi administrasi pertanahan, tanpa dibarengi dengan skema pendampingan yang memadai, berisiko menggusur kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan.
Bagi ODGJ, lansia, masyarakat miskin, atau kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman hukum dan akses terhadap sumber daya, proses sertifikasi tanah bisa menjadi medan yang menakutkan dan memberatkan. Biaya, kerumitan birokrasi, dan kurangnya informasi adalah hambatan yang seringkali tidak dapat mereka atasi sendiri.
Oleh karena itu, kebijakan semacam ini menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dan inklusif. Pemerintah perlu proaktif dalam:
- Menyediakan Layanan Pendampingan Hukum Gratis: Membentuk tim pendampingan yang terdiri dari advokat, mahasiswa hukum, atau relawan terlatih untuk membantu kelompok rentan dalam proses pengurusan legalitas tanah.
- Sosialisasi yang Adaptif: Melakukan sosialisasi kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan media yang tepat sasaran, dan menjangkau langsung ke komunitas yang terdampak.
- Skema Biaya yang Berkeadilan: Memberikan keringanan atau bahkan pembebasan biaya BPHTB dan biaya administrasi lainnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan.
- Memperpanjang Tenggat Waktu atau Memberikan Solusi Alternatif: Meninjau kembali tenggat waktu penghapusan Letter D, atau menyediakan solusi alternatif yang memastikan hak-hak masyarakat tidak terampas.
Tanpa langkah-langkah konkret ini, perubahan regulasi pertanahan dapat meninggalkan jejak ketidakadilan, di mana mereka yang paling membutuhkan justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Perlindungan hak atas rumah dan tanah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal kemanusiaan dan jaminan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.