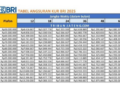JAKARTA,
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 telah memicu perhatian serius dari organisasi lingkungan hidup. Dua lembaga utama, Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan bahwa kejadian ini bukan sekadar fenomena cuaca aneh, melainkan tanda nyata dari krisis iklim yang semakin mengancam.
Greenpeace dan Walhi menilai bahwa bencana tersebut adalah hasil dari kerusakan ekosistem yang berlarut-larut, dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang cenderung ekstraktif. Mereka menekankan bahwa penurunan daya dukung lingkungan akibat aktivitas pertanian skala besar, tambang, dan pembangunan infrastruktur seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi penyebab utama kejadian ini.
Fenomena Siklon Tropik Senyar dan Kerusakan Ekologis
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, menjelaskan bahwa fenomena Siklon Tropik Senyar, yang biasanya jarang terjadi di daerah Khatulistiwa, membawa curah hujan ekstrem. Namun, dampak kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada cuaca, tetapi juga mencerminkan kondisi lingkungan yang sangat kritis.
Menurut Arie, hampir semua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Sumatra dalam kondisi kritis, dengan tutupan hutan alam kurang dari 25 persen. Hal ini jauh di bawah batas ideal yang seharusnya mencapai 30 persen sesuai Undang-Undang Kehutanan sebelum Omnibus Law diundangkan.
Salah satu contoh paling tragis adalah DAS Batang Toru di Sumut. Di wilayah hulu DAS tersebut, deforestasi besar-besaran terjadi akibat pertanian dan perkebunan. Sementara itu, di bagian tengah DAS yang masih memiliki hutan, aktivitas tambang dan PLTA juga turut merusak ekosistem.
“Kombinasi antara kehancuran di hulu dan topografi sungai yang curam dan pendek menciptakan karakteristik banjir bandang yang disertai longsoran,” kata Arie. Ia menambahkan bahwa fungsi hutan sebagai penahan air sudah menurun drastis, sehingga material kayu dan tanah langsung terbawa, menyebabkan sedimentasi parah dan mengancam jiwa.
Desakan untuk Evaluasi Kebijakan Ekstraktif
Greenpeace secara tegas mendesak pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan berbasis ekstraktivisme dan pertanian skala besar. Mereka mengecam pandangan yang masih menganggap sumber daya alam sebagai aset ekonomi yang harus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
“Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan mencapai 8% justru akan memperluas ekspansi investasi yang merusak. Ekonomi yang kita bangun akan dihancurkan dalam sekejap jika bencana datang,” kritik Arie.
Penetapan Bencana Nasional dan Pemulihan Jangka Panjang
Sebagai respons cepat, Greenpeace juga mengajukan permohonan agar pemerintah segera menetapkan bencana di Sumatra sebagai Bencana Nasional. Penetapan ini dinilai penting agar sumber daya dapat segera terintegrasi untuk membantu korban yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan yang masih hilang.
“Pendekatan bencana pemerintah selama ini reaktif. Pemerintah harus memastikan distribusi bantuan segera sampai dan ada kebijakan terintegratif untuk pemulihan ekologi jangka panjang di wilayah DAS yang sudah kritis,” ujar Arie.
Tanggapan dari Walhi: Potensi Bencana Ekologis di Seluruh Indonesia
Senada dengan Greenpeace, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, menyatakan bahwa bencana di Sumatra adalah refleksi dari potensi bencana ekologis yang besar di seluruh Indonesia. Menurut Walhi, setiap wilayah memiliki kerentanan masing-masing, sesuai dengan karakteristik ekosistemnya.
“Kawan-kawan yang berada di daerah pegunungan atau dengan kelerengan lebih dari 30 derajat rawan banjir dan longsor. Dan ini tidak hanya terjadi di Sumatera,” katanya.
Walhi secara tegas menyebut beberapa wilayah padat penduduk dan industri sebagai kawasan yang “merisikan” bencana ekologis di masa depan. Mereka menyoroti wilayah Jawa yang memiliki tutupan hutan kurang dari 30 persen, serta Sulawesi dengan aktivitas tambang yang meningkat pesat.
“Hampir seluruh wilayah Jawa yang tutupan hutannya atau areal hutannya kurang dari 30 persen itu rawan banget dengan kebencanaan. Lalu kita masuk lagi di Sulawesi, dengan aktivitas tambang-tambang mineral kritis yang terus meningkat, ini berpotensi juga melahirkan kebencanaan,” tegas Boy.
Ia menuntut pemerintah untuk serius memanfaatkan teknologi dan memantau tren cuaca ekstrem guna mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.