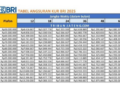Setiap Kamis pagi, pemandangan tak biasa tersaji di gerbang sekolah. Yono, seorang siswa kecil, melangkah masuk dengan atribut yang jauh dari kata lazim. Seragam sekolahnya rapi, tas punggung terpasang kokoh, namun yang paling mencuri perhatian adalah helm bekas milik ayahnya yang bertengger di kepalanya. Helm tua itu, dengan cat yang sudah terkelupas dan aroma bensin serta oli yang masih samar tercium, bukanlah sebuah pernyataan gaya, melainkan sebuah bentuk ikhtiar.
Sesampainya di depan gerbang, langkah Yono dihentikan oleh guru piket. “Yono… itu kenapa pakai helm?” tanyanya, mungkin sedikit heran namun tetap berusaha menjaga nada profesional. Yono menjawab dengan ketenangan luar biasa, seolah pertanyaan itu terlalu mendasar untuk dijawab. “Hari Kamis, Pak.”
Guru piket masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. “Terus?”
“Pelajaran musik,” jawab Yono singkat.
Sang guru piket hanya bisa menghela napas panjang, lalu mengantar Yono menuju ruang kepala sekolah. Di sana, suasana mendadak berubah menjadi lebih formal. Kepala sekolah, dengan kacamata tebal bertengger di hidungnya, menatap Yono dengan tatapan penuh tanya.
“Yono, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini?”
“Tahu, Pak,” jawab Yono tanpa keraguan.
“Kenapa?”
“Karena saya pakai helm.”
“Kenapa pakai helm?” kali ini pertanyaan itu diucapkan dengan nada yang sedikit lebih mendesak.
Tanpa menunggu instruksi lebih lanjut, Yono menarik sebuah kursi, duduk dengan tegak, dan mulai menjelaskan. Cara bicaranya bukan lagi seperti seorang murid biasa, melainkan seperti seorang petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sedang memberikan presentasi. “Ini soal keselamatan, Pak.”
Kepala sekolah mengerutkan keningnya. “Keselamatan dari apa?”
“Not balok, Pak.”
“Not balok?” Kepala sekolah mengulang, terdengar bingung.
“Iya, Pak. Di papan tulis. Notnya sih tidak apa-apa. Tapi itu ada baloknya. Kalau dilempar, bisa berdarah.”
Keheningan menyelimuti ruangan. Kepala sekolah mencoba mencari logika lain dalam penjelasan Yono. “Tapi guru musik tidak melempar balok.”
Yono mengangguk sopan. “Belum, Pak. Tapi pencegahan itu penting.” Ia melanjutkan, semakin percaya diri, “Bapak kan sering bilang, safety first.”
Kepala sekolah terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terbelalak. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. “Daripada nanti kenapa-kenapa,” tambah Yono, “lebih baik siap dari awal.”
Tidak ada jawaban lagi. Dalam perdebatan yang tidak terucapkan ini, Yono dan helmnya jelas memenangkan pertarungan logika.
Di dalam kelas seni musik, Yono mengambil tempat duduk di bangku paling depan. Helmnya masih terpasang di kepala, posisinya tegak, ia merasa aman. Guru mulai menjelaskan tentang tangga nada. Suaranya lembut, ritmenya pelan, terdengar seperti alunan pengantar tidur. Yono merasa sangat nyaman. Terlalu nyaman, bahkan.
Beratnya helm di kepala, dikombinasikan dengan kehangatan ruangan dan suara guru yang menenangkan, perlahan membuat kelopak mata Yono memberat. Ia pun terlelap di tengah alunan musik.
Beberapa menit kemudian, sebuah suara keras memecah keheningan kelas. “Plak!”
Sebuah penghapus papan tulis dengan rangka kayu yang cukup besar melayang di udara dan mendarat tepat di atas helm Yono. Seluruh kelas terkejut. Yono terbangun seketika, refleks berdiri. Ia menepuk-nepuk helmnya, lalu dengan polos dan lantang berseru, “Untung pakai helm! Not balok gagal melukai kepalaku!”
Sontak, seluruh kelas pecah dalam tawa. Guru musik terpaku di tempatnya, terkejut dengan kejadian yang tak terduga itu. Kepala sekolah, yang kebetulan lewat di depan kelas, hanya bisa menutup wajahnya sendiri dengan kedua tangannya.
Sejak hari itu, tidak ada lagi seorang pun di sekolah itu yang berani menertawakan helm Yono pada hari Kamis. Karena di sekolah itu, hanya ada satu murid yang benar-benar memahami dan menerapkan prinsip safety first dengan cara yang paling literal dan tak terbantahkan. Yono, dengan helmnya, telah mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang kesiapan dan pencegahan, meskipun dengan cara yang paling unik dan menghibur.