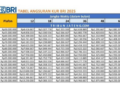Bencana seharusnya menjadi momen di mana solidaritas bertindak lebih cepat daripada sorotan kamera, dan empati hadir lebih kuat daripada simbolisme politik. Namun, kenyataan yang terjadi saat banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat justru menampilkan serangkaian adegan yang lebih menyerupai panggung pencitraan daripada aksi kemanusiaan yang tulus.
Di tengah penderitaan warga yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan harta benda, beberapa pejabat publik justru terlihat memanfaatkan momen ini sebagai kesempatan untuk membangun citra personal atau politik. Beberapa contoh yang mencolok antara lain:
Seorang menteri koordinator terlihat seorang diri memanggul sekarung beras, seolah-olah menjadi relawan lapangan. Aksi ini, meskipun mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan kepedulian, justru menimbulkan kesan bahwa bencana dijadikan ajang untuk mencari perhatian.
Seorang anggota DPR tampil dengan rompi yang menyerupai rompi anti peluru, lengkap dengan name tag, saat mengunjungi lokasi banjir. Penampilan ini memberikan kesan dramatis yang berlebihan dan tidak relevan dengan kebutuhan mendesak para korban banjir.
Putri seorang pejabat tinggi negara, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, terlihat dalam video sedang membersihkan rumah warga. Meskipun tindakan membersihkan rumah warga adalah tindakan positif, namun menjadi problematis ketika dikemas dan disebarluaskan seolah-olah menjadi konten visual untuk konsumsi publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di balik tindakan tersebut. Apakah benar-benar untuk membantu korban banjir, atau hanya untuk meningkatkan citra publik?
Fenomena serupa juga muncul dari sejumlah pejabat publik lainnya. Praktik ini bukan sekadar masalah gaya, tetapi juga menyinggung isu etika kepemimpinan publik. Pemimpin memegang mandat untuk melaksanakan tindakan kolektif yang berlandaskan kepentingan publik, bukan untuk memproduksi narasi visual demi keuntungan politik sesaat.
Ketika aksi-aksi simbolik mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kerja sistematis, kesan yang muncul adalah bencana dijadikan sebagai panggung politik. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori political symbolism dan disaster politics. Banyak pemimpin memanfaatkan kondisi krisis sebagai momen untuk menunjukkan citra tanggap dan peduli kepada rakyat. Namun, tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan tanpa koordinasi lintas lembaga yang efektif, tindakan-tindakan simbolik hanya melahirkan “kepemimpinan performatif”.
Dalam konteks inilah publik kerap melihat pejabat turun ke lapangan bukan sebagai bagian dari manajemen krisis yang komprehensif, tetapi sebagai kesempatan untuk tampil di depan kamera. Padahal, kepemimpinan dalam situasi bencana membutuhkan hal yang jauh lebih substansial, mulai dari perencanaan mitigasi, sistem logistik yang responsif, kesiapsiagaan daerah, alokasi anggaran yang tepat, hingga koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah.
Korban banjir tidak membutuhkan drama heroik sesaat, melainkan jaminan bahwa mereka akan memperoleh bantuan secara cepat, tepat, dan merata. Dalam standar internasional penanganan bencana, seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, pemimpin ideal justru dituntut untuk memastikan tata kelola bencana berjalan berdasarkan protokol dan sains, bukan berdasarkan kamera.
Pemimpin harus mampu mengomunikasikan informasi yang akurat, menggerakkan sumber daya secara efektif, meminimalkan risiko politik terhadap relawan, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran. Bukan tampil memanggul beras atau membersihkan rumah demi viral di media.
Pencitraan di tengah bencana dapat merusak kepercayaan publik. Ketika warga melihat bantuan disalurkan dengan membawa nama partai, foto pribadi, atau rombongan pejabat yang datang lebih banyak untuk berswafoto ketimbang bekerja, maka yang tergerus bukan hanya kredibilitas perorangan, tetapi juga legitimasi institusi negara. Bahkan dalam jangka panjang akan menyebabkan rendahnya akuntabilitas, lemahnya partisipasi warga, dan meningkatnya sinisme terhadap pemerintah.
Sudah saatnya pejabat publik menempatkan bencana pada konteks yang seharusnya, yaitu sebagai peristiwa kemanusiaan, bukan panggung politik. Bantuan harus disalurkan tanpa label, tanpa simbol partai, dan tanpa memposisikan warga terdampak sebagai latar belakang drama kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang membiarkan kinerja berbicara, bukan kamera.
Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki standar kepemimpinan krisis. Dengan mengedepankan empati, profesionalisme, serta tata kelola penanganan bencana yang berbasis data dan prosedur, pemerintah dapat memulihkan kembali kepercayaan warga. Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi mempermalukan korban dengan pencitraan murahan adalah bentuk krisis moral yang sepenuhnya dapat dicegah. Bantuan untuk korban harus tetap menjadi prioritas. Segala hal lainnya, termasuk pencitraan politik, seharusnya dikesampingkan.