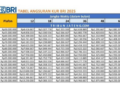Kembalinya Polisi Aktif di Jabatan Sipil: Menggugat Prinsip Demokrasi dan Birokrasi Sehat
Isu penempatan anggota kepolisian aktif dalam jabatan-jabatan sipil kembali mencuat ke permukaan, memicu perdebatan publik yang hangat. Permasalahan ini bukan sekadar urusan administratif kepegawaian semata, melainkan menyentuh inti dari tata kelola pemerintahan demokratis. Tiga pilar utama yang dipertaruhkan adalah prinsip supremasi sipil, meritokrasi dalam birokrasi, serta netralitas aparatur negara, terutama dalam konteks pemilihan umum.
Dalam kerangka negara demokrasi modern, birokrasi sipil merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Fondasinya dibangun atas prinsip profesionalisme, jenjang karier yang jelas, pelatihan yang memadai, dan kompetensi teknokratik yang mendalam. Ketika jabatan-jabatan sipil yang krusial justru diisi oleh personel kepolisian yang masih aktif, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aparatur sipil negara (ASN) yang merasa terpinggirkan, tetapi juga merusak arsitektur fundamental pemerintahan negara itu sendiri.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 secara tegas menggarisbawahi prinsip pemisahan yang jelas antara fungsi sipil dan fungsi keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diposisikan sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, bukan sebagai pemain dalam ranah birokrasi sipil. Ketika anggota Polri yang masih aktif menduduki jabatan sipil—terlebih lagi tanpa melepaskan statusnya dari institusi kepolisian—terjadi sebuah “tumpang tindih kewenangan” (overlapping authority) yang sangat berbahaya.
Supremasi sipil bukanlah sekadar slogan normatif belaka. Ia adalah mekanisme kontrol kekuasaan yang vital, memastikan bahwa aparat bersenjata tidak memiliki “loyalitas ganda” (dual loyalty) yang dapat menimbulkan konflik, yaitu antara institusi asalnya dan jabatan sipil yang diembannya. Jika batasan ini menjadi kabur, risiko konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan akan terbuka lebar.
Tercederainya Sistem Meritokrasi ASN
Lebih jauh lagi, praktik semacam ini secara serius melukai sistem merit yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun dalam birokrasi Indonesia. Para ASN meniti karier mereka melalui serangkaian proses yang ketat, meliputi pendidikan, pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja yang objektif, dan seleksi terbuka untuk promosi. Ketika posisi puncak justru diisi oleh individu dari luar sistem ASN, pesan yang diterima oleh seluruh jajaran birokrasi sangatlah jelas: kompetensi teknis dan loyalitas profesional tidak lagi menjadi faktor penentu utama.
Konsekuensi yang tak terhindarkan dari situasi ini adalah demotivasi di kalangan ASN. Aparatur sipil, yang seharusnya menjadi motor penggerak roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, justru merasa terasing di “rumah” mereka sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan melemahkan kapasitas institusional negara secara keseluruhan.
Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang panjang ketika militer memainkan peran dominan dalam berbagai urusan sipil dengan label “dwi-fungsi ABRI”. Pengalaman masa lalu tersebut menunjukkan bahwa dominasi militer dalam ranah sipil tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, apalagi demokratis. Sebaliknya, ia justru melahirkan birokrasi yang sangat hierarkis, tertutup, dan minim kontrol publik.
Oleh karena itu, kekhawatiran publik saat ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Penempatan polisi aktif di jabatan sipil—meskipun terkadang dibungkus dengan dalih kebutuhan akan keahlian dalam penegakan hukum atau penugasan khusus—secara sosiologis dan politis membangkitkan kembali trauma masa lalu yang belum sepenuhnya pulih.
Menata Ulang Birokrasi dengan Kepala Dingin
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil patut diapresiasi. Keputusan ini bukan sekadar koreksi hukum semata, melainkan sebuah penegasan arah menuju penataan cara bernegara yang lebih sehat dan profesional.
Namun, putusan hukum semata tidaklah cukup. Tanpa kemauan politik yang kuat dan konsistensi dalam pelaksanaannya, praktik lama berpotensi untuk terus berulang dalam bentuk dan nama yang berbeda, yang terkadang disebut sebagai “multi-fungsi aparat keamanan”.
Pemerintah perlu menunjukkan sikap yang tegas dan jernih. Apabila suatu jabatan dikategorikan sebagai jabatan sipil, maka mekanisme pengisiannya harus sepenuhnya tunduk pada sistem ASN dan prinsip meritokrasi. Jika negara memang membutuhkan keahlian spesifik dari aparat kepolisian, maka jalur yang seharusnya ditempuh adalah pengunduran diri, transisi status kepegawaian, dan proses seleksi terbuka yang transparan.
Pada saat yang bersamaan, Polri juga perlu memperkuat reformasi internalnya agar karier anggotanya tidak “bocor” ke wilayah sipil yang bukan merupakan mandat institusionalnya. Profesionalisme kepolisian, menurut hemat saya, justru akan semakin kokoh jika institusi ini fokus pada fungsi utamanya: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, tanpa pandang bulu dan tanpa campur tangan dalam proses politik seperti pemilihan umum.
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil bukanlah persoalan siapa individu yang menduduki jabatan tersebut, melainkan lebih kepada soal sistem dan prinsip bernegara yang sehat. Pemerintahan yang demokratis tidak boleh dikendalikan oleh pragmatisme jangka pendek yang mengorbankan prinsip-prinsip jangka panjang.
Jika hati birokrasi terus dilukai oleh praktik-praktik semacam ini, janganlah heran jika pemikiran inovatif tidak akan pernah lahir, dan semangat pengabdian akan merosot drastis. Aparatur negara mungkin hanya akan bekerja seadanya, menerapkan prinsip “business as usual”. Lebih jauh lagi, hal ini akan berujung pada melemahnya kualitas pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Penataan birokrasi negara menuntut konsistensi, keberanian politik, dan penghormatan yang mendalam terhadap batas-batas kewenangan institusi yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Di sanalah masa depan kehidupan pemerintahan Indonesia yang sesungguhnya dipertaruhkan.